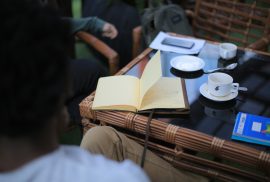Oleh: Muhammad Nurrifqi Fuadi | Penyunting: Muhammad Ikbal Wahyu Sukron, S.Psi., M.A.
Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital terutama internet dan media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan mengatur kehidupan sehari-hari. Berbagai platform digital dan perangkat canggih telah menawarkan akses yang lebih luas sehingga kebermanfaatannya bisa dirasakan dengan baik. Namun, di tengah manfaat yang dirasakan, individu di usia dewasa awal yang sedang mencari identitas dan membangun karier menghadapi tantangan baru yaitu sulitnya memiliki pengendalian diri dengan baik (Sheppard dkk., 2020). Self-control atau pengendalian diri menjadi semakin penting khususnya dalam konteks dewasa awal karena kemajuan digital seringkali memperkenalkan godaan dan gangguan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu. Pengembangan kemampuan pengendalian diri perlu dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan potensi dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Terdapat beberapa dampak negatif penggunakan teknologi pada individu, khususnya di usia dewasa awal. Penelitian menunjukan bahwa peningkatan penggunaan perangkat digital berdampak pada kesehatan mental dengan meningkatkan resiko kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri (Ramadani, 2024). Fasilitas berupa internet dan media sosial membuat individu terjebak pada aktivitas seperti perilaku bermalas-malasan dengan mengakses internet (cyberloafing) di tempat kerja atau di ruang kelas (Duhita & Daellenbach, 2016); munculnya perasaan FoMO (Przybylski dkk., 2013); adiksi penggunaan media sosial (Andreassen dkk., 2017); kelelahan akibat bermedia sosial (Zhang dkk., 2021); perilaku membeli secara impulsif (Verplanken & Sato, 2011); adiksi judi online (Mcquade & Gill, 2012); dan masih banyak lagi.
Pengendalian diri sangat berperan penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan gangguan tersebut. Pentingnya melakukan pengendalian diri terletak pada kemampuan seseorang untuk menunda kepuasan jangka pendek demi mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan definisi pengendalian diri yang dimaknai sebagai “the ability to subdue immediate desires to achieve long-term goals” (Aronson dkk., 2019). Penelitian longitudinal yang dilakukan Walter Mischel (dalam Lange dkk., 2012) menemukan bahwa partisipan yang memiliki kemampuan pengendalian diri untuk menunda kepuasan (delay gratification) menunjukan kehidupan yang lebih terarah dan sejahtera di masa depan. Hal ini ditunjukkan dengan fungsi kognitif dan sosial yang lebih baik, pendidikan dan kehidupan ekonomi yang lebih baik, tidak rentan mengalami permasalahan kesehatan mental hingga kemungkinan kecil mengalami self-esteem dan self-worth rendah.
Meskipun demikian, pengendalian diri merupakan perilaku yang tidak mudah untuk dicapai. Menurut Branscombe dan Baron (2023), saat melakukan pengendalian diri, individu sering kali merasa kelelahan sehingga membuat perilaku pengendalian diri berikutnya terasa lebih sulit dan berat. Kondisi ini terjadi karena ego depletion, yaitu penurunan kemampuan pengendalian diri yang dialami oleh individu setelah usaha keras yang telah dilakukan untuk pengendalian diri sebelumnya. Akibatnya, individu cenderung merespons dan bertindak dengan cara yang sama, meskipun menerima pesan persuasif dengan argumen yang kuat maupun lemah. Padahal, idealnya, individu seharusnya dapat mengendalikan diri, memilih pesan persuasif yang memiliki argumen kuat, dan mengabaikan pesan dengan argumen yang lemah.
Lalu apakah pengendalian diri itu bisa dibentuk. Bagaimana proses pembentukan pengendalian diri. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan agar memiliki pengendalian diri yang baik menurut Branscombe dan Baron (2023):
- Melakukan pelatihan pengaturan diri. Latihan dilakukan dengan meredam godaan dan mempertahankan perilaku penundaan secara adaptif hingga menjadi perilaku yang otomatis dan refleks.
- Jangan lupa berikan jeda waktu untuk istirahat antara tugas pengendalian diri yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ego depletion.
- Pikirkan secara abstrak tujuan yang ingin kita capai. Hal ini membantu untuk mengingat kembali rencana yang sudah kita buat dan menghindari melakukan apa yang tidak direncanakan.
Pembentukan pengendalian diri yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran umum yang perlu diikuti dengan perilaku dan teknik yang lebih spesifik, sesuai dengan fase kehidupan individu. Setiap individu menghadapi tantangan yang berbeda, tergantung pada tugas dan fungsi perkembangannya. Satu hal yang menjadi perhatian bersama adalah kemajuan digital sering kali disertai dengan berbagai gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan pengendalian diri diperlukan di tengah tantangan perkembangan digital sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih terarah, sehat, dan produktif. Langkah ini penting agar kita tidak hanya menghindari godaan, tetapi juga dapat mencapai tujuan dan kesejahteraan yang kita inginkan.
Referensi
Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287–293. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.03.006
Aronson, E., Wilson, T. D., & Sommers, S. R. (2019). Social psychology (Tenth Edition). Pearson.
Branscombe, N. R., & Baron, R. A. (2023). Social psychology (Fifteenth Global). Pearson.
Duhita, S., & Daellenbach, U. (2016). “Is loafing at work necessarily detrimental? a study of loafing, job productivity and satisfaction.” Academy of Management Proceedings, 2016(1), 15471. https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.15471abstract
Lange, P. A. M. Van, Kruglanski, A. W., & Higgins, E. T. (2012). Handbook of theories of social psychology (Vol. 2). SAGE Publications.
Mcquade, A., & Gill, P. (2012). The role of loneliness and self-control in predicting problem gambling behaviour. Gambling Research: Journal of the National Association for Gambling Studies (Australia)., 24 (1) Gambling Research, 24(1), 18–30. https://vuir.vu.edu.au/30358/
Przybylski, A. K., Murayama, K., Dehaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
Ramadani, Refik. (2024). The impact of technology use on young people: A case study of social media and internet usage. Asian Journal of Research in Computer Science 17 (8):13-23. https://doi.org/10.9734/ajrcos/2024/v17i7486.
Sheppard, S., Hood, M., & Creed, P. A. (2020). An identity control theory approach to managing career identity in emerging adults. Emerging Adulthood, 8(5), 361-366. https://doi.org/10.1177/2167696819830484
Verplanken, B., & Sato, A. (2011). The psychology of impulse buying: An integrative self-regulation approach. Journal of Consumer Policy, 34(2), 197–210. https://doi.org/10.1007/s10603-011-9158-5Zhang, S., Shen, Y., Xin, T., Sun, H., Wang, Y., Zhang, X., & Ren, S. (2021). The development and validation of a social media fatigue scale: From a cognitive behavioral- emotional perspective. In PLoS ONE (Vol. 16, Issue 1 January). Public Library of Science. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245464