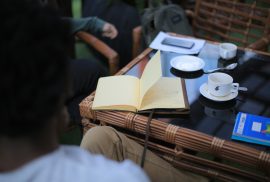Oleh: Rahmita Laily Muhtadini | Penyunting: Fakhirah Inayaturrobbani S.Psi, M.A
Perkawinan anak merupakan salah satu isu serius negara Indonesia yang perlu mendapat perhatian lebih. Sebab, Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dengan jumlah perkawinan anak terbesar mencapai 25,53 juta jiwa (UNICEF, 2023). Berdasarkan data Kemen PPPA (2021) jumlah perempuan indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 10,35%. Artinya, 1 dari 10 perempuan di Indonesia pernah melakukan perkawinan anak. Tingginya angka perkawinan anak ini, menjadi isu yang perlu untuk disorot dan diselesaikan.
Berbagai risiko tinggi dari perkawinan anak dapat mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan, dan hak hidup anak. Perkawinan anak dapat meningkatkan kehamilan berisiko tinggi, kelahiran prematur, keguguran, pendarahan hingga kematian pada ibu (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Selain itu, perkawinan anak akan membuat kesempatan anak melanjutkan pendidikan menjadi terhenti, kehilangan kesempatan bekerja, meningkatkan resiko perceraian dan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta memunculkan kemungkinan hidup di bawah garis kemiskinan (Kemen PPPA, 2021).
Melihat tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia dan risiko buruk yang harus dihadapi, maka perlu adanya langkah dan kerja sama berbagai pihak untuk memutus rantai perkawinan anak. Mewujudkan kehidupan anak yang terbebas dari bayangan perkawinan anak, tidak dapat dilakukan hanya dengan berpusat pada pemerintah saja. Namun juga, membutuhkan kolaborasi antar pihak dan seluruh elemen dari lapisan masyarakat. Kolaborasi bisa dilakukan mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, pihak sekolah, masyarakat sipil, serta para ahli.
Orang tua berperan penting dalam peningkatan kasus perkawinan anak karena mereka yang menjadi penentu utama arah kehidupan anak di masa depan. Beberapa motivasi orang tua yang mendasari keputusan menikahkan anak di bawah umur antara lain: adanya kesalah pola pikir yang menganggap menikahkan anak akan membuat mereka terhindar dari pergaulan dan seks bebas, adanya ketakutan orang tua jika anak mendapatkan label ‘tidak laku’ maupun ‘perawan tua’ karena belum menikah, dan orang tua memutuskan menikahkan anak jika terjadi kehamilan di luar nikah (Syalis & Nurwati, 2020; Desiyanto, Fajar, & Risqi, 2022; Taher, 2022). Selain itu, terdapat orang tua yang menganggap menikahkan anak sedini mungkin, akan membebaskan mereka dari beban tanggung jawab membesarkan dan membiayai anak (Chae & Ngo, 2017). Pemikiran-pemikiran orang tua yang salah, serta adanya pengaruh budaya di lingkungan sekitar anak, akan memperbesar kemungkinan terjadinya keputusan perkawinan dini (Kemen PPPA, 2021).
Orang tua perlu bijaksana untuk tidak menikahkan anak di usia dini. Mencegah hal tersebut, orang tua perlu mendapatkan dan memberikan edukasi tentang bahaya dan risiko melakukan perkawinan anak, serta edukasi kesehatan reproduksi yang dianggap selama ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan porno oleh budaya setempat (Taher, 2022). Pemberian edukasi ini, sangat diperlukan agar orang tua dapat menjadi tameng bagi anak, serta memberikan kesadaran pada anak untuk mempertimbangkan sendiri risiko negatif dari pernikahan dini.
Selain itu, keberadaan tokoh masyarakat sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian Mauludi (2023) menemukan para tokoh masyarakat ini dapat memberikan penjelasan tentang syarat-syarat pernikahan menurut agama, serta memberikan edukasi pentingnya mematuhi aturan hukum perkawinan di Indonesia. Tokoh masyarakat juga dapat memberikan pemahaman kepada anak mengutamakan pendidikan dan melakukan pengembangan diri sebelum menikah.
Pihak sekolah juga berkontribusi membentuk cara pikir anak dalam memandang pentingnya meraih pendidikan. Sebagai institusi yang menjadi rumah kedua bagi anak, sekolah perlu memberikan fasilitas agar anak bisa melakukan pengembangan diri, memberikan edukasi kesehatan reproduksi, dan membekali anak dengan hard skill dan soft skill, sehingga anak bisa berdaya dalam menentukan masa depannya. Sekolah juga dapat memberikan pemahaman, agar anak berusaha menyelesaikan pendidikannya, karena pemahaman yang salah meningkatkan kemungkinan anak melakukan perilaku berisiko dan pernikahan dini (Rosyidah & Fajriyah, 2013).
Selanjutnya, masyarakat sekitar perlu untuk mendorong anak agar bisa memaksimalkan potensinya, mencegah anak masuk ke dalam lingkungan yang buruk, dan mematahkan stigma negatif ketika anak tidak segera tentang pernikahan. Sebab, anak dan remaja selalu hidup berdampingan dengan sistem di sekitarnya, seperti: keluarga, tetangga, sekolah, komunitas, dan juga negara (McWhirter et al, 2017). Apabila lingkungan terdekat anak memegang nilai-nilai yang salah tentang perkawinan, maka segala usaha untuk mencegah perkawinan anak akan sia-sia.
Namun, apabila perkawinan anak telah terjadi, maka perlu memberikan penangan yang sifatnya memperbaiki atau mengembalikan situasi menjadi lebih baik. Ugboha dan Namo (2019) menemukan bahwa pusat konseling, rehabilitasi, dan pelayanan pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu korban perkawinan anak bisa pulih dan belajar menjalani kehidupan bersama masyarakat. Para konselor juga dapat melakukan konseling keluarga untuk memberikan dukungan emosional, mengatasi keluarga yang disharmoni, meminimalisir KDRT, serta mengurangi bercerai pada kasus perkawinan nak (Rohman & Annajih, 2021).
Menyelamatkan hak hidup anak dari perkawinan di usia dini harus dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi ini dibutuhkan agar membentuk lingkungan yang mendukung anak mendapatkan hak-haknya dan memfasilitasi anak agar dapat memaksimalkan potensi dirinya. Sehingga, anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi generasi penerus bangsa yang bebas dari bayang-bayang perkawinan anak. Sebab, setiap anak memiliki hak untuk bisa menggapai impian dan membuat masa depannya cerah, tanpa harus direnggut kebebasannya dengan menikah sebelum menginjak usia yang matang.
Referensi
Chae, S., & Ngo, T. (2017). The global state of evidence on interventions to prevent child marriage. GIRL Center Research Brief no. 1. New York: Population Council. https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1540&context=departments_sbsr-pgy
Desiyanto, J., Fajar, A., & Risqi, R. (2022). Pendidikan Orang Tua terhadap Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur. Progressive of Cognitive and Ability, 1(2), 167-175.https://doi.org/10.56855/jpr.v1i2.41
Mauludi, S. (2023). Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru. Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora, 2(1), 13-22. https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69
McWhirter, J. J., McWhirter, B. T., McWhirter, A. M., & McWhirter, E. H. (1994). High and low-risk characteristics of youth : The five Cs of competency. Elementary School Guidance & Counseling, 28(3), 188-196. https://www.jstor.org/stable/42869153
Kemen PPPA. (2021). Profil anak indonesia 2018. Jakarta: KPPA. https://dispppa.lampungtengahkab.go.id/upload/dokumen/8ebef-profil-anak-indonesia-2019.pdf
Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(4), 275-283. https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672
Rosyidah, I., & Fajriyah, I. M. D. (2013). Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat. Harmoni, 12(2), 59-71. https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/175/149
Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(1), 29-39. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192
Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. Indonesia. Journal of Midwifery Sciences, 1(3), 100-110. https://doi.org/10.53801/ijms.v1i3.46Ugboha, G. O., & Namo, I. S. (2019). Effect of Early Marriage on Girl-Child’s Further Education in Okpokwu Local Government Area, Nigeria: Implications for Counseling. KIU Journal of Humanities, 4(1), 65-72. https://ijhumas.com/ojs/index.php/niuhums/article/view/461