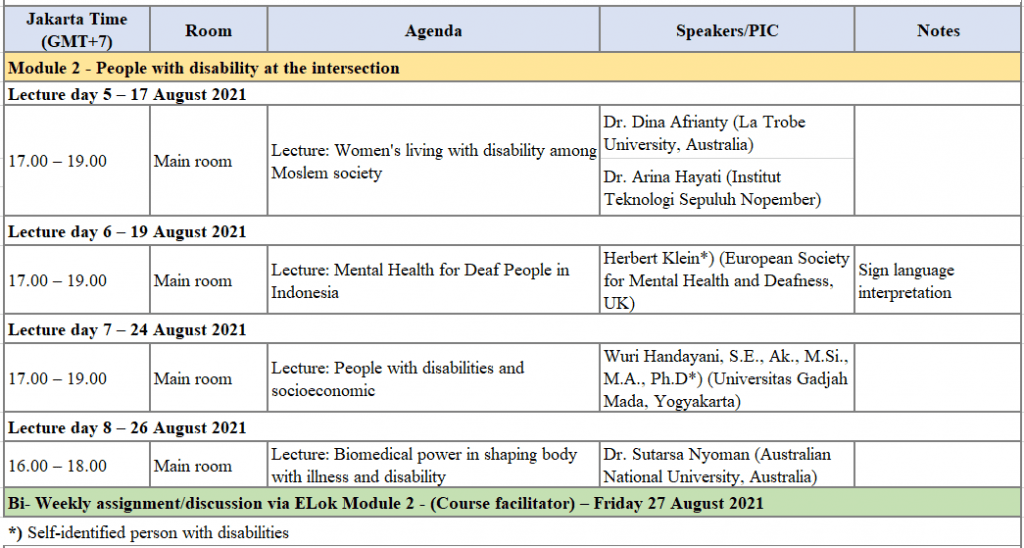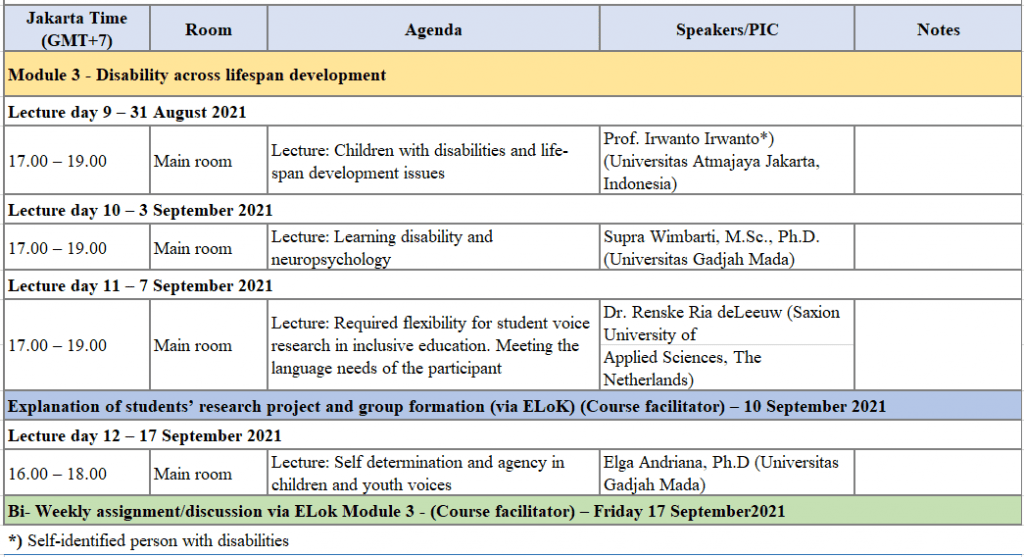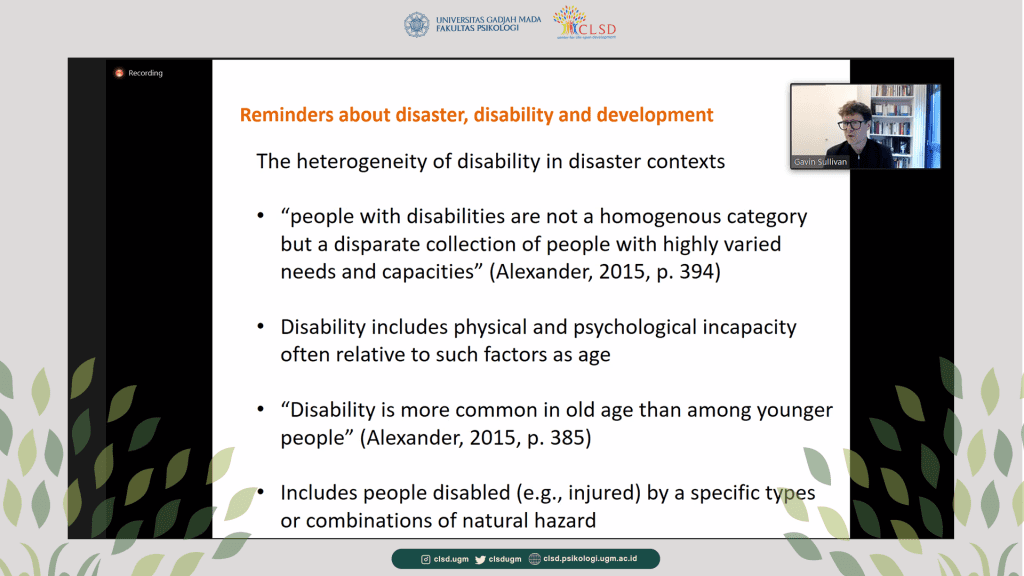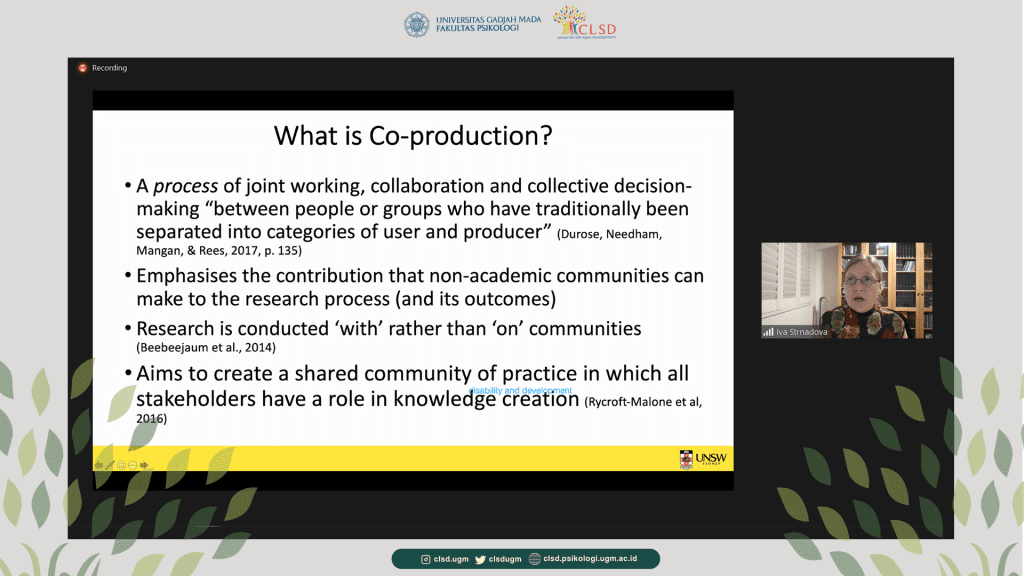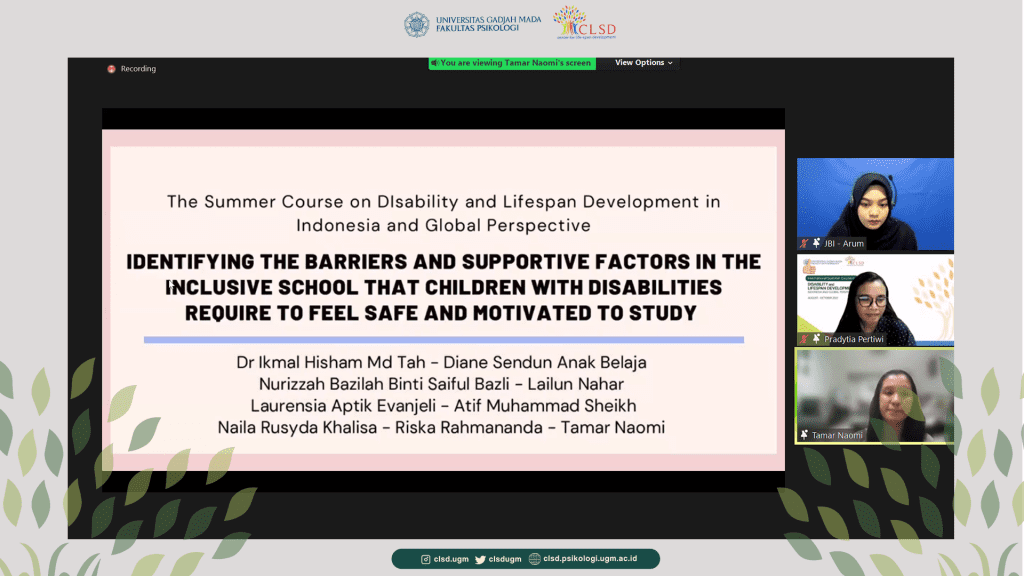Mendukung Hubungan Sehat Pada Dewasa Muda dengan Disabilitas, Bagaimana Caranya?
oleh: Munadira
editor: Resti Fahmi Dahlia

Photo by Ivan Samkov from Pexels
Cinta adalah perasaan natural yang dirasakan oleh tiap individu. Usia dewasa muda kerap dikaitkan dengan usia dimana hubungan romantis menjadi suatu kebutuhan. Hubungan percintaan memungkinkan kita untuk tetap terhubung satu sama lain dan juga melindungi kita dari perasaan kesepian (Ignagni, dkk., 2016). Serupa dengan individu pada umumnya, kebutuhan terkait mencintai dan dicintai juga dirasakan oleh individu dengan disabilitas. Kebutuhan mereka akan cinta dan koneksi sering kali dipertanyakan atau bahkan dipandang salah oleh mereka yang tidak memiliki disabilitas. Mereka seringkali mengalami stereotip budaya dan prasangka yang menyakitkan dan merusak kepercayaan diri. Mereka yang hidup dengan disabilitas juga terkadang diharapkan untuk menjalin hubungan “dengan jenisnya sendiri”. Menurut penelitian yang dilakukan Friedman (2019), partisipan penelitiannya yang merupakan individu dengan disabilitas mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan lawan jenis, terutama hubungan yang bersifat jangka panjang. Selain itu, mereka juga mendapatkan stigma bahwa mereka seharusnya menjalin hubungan dengan sesama individu dengan disabilitas.
Hubungan romantis yang dijalani oleh individu dengan disabilitas adalah sebuah kondisi yang menjadi perhatian dari banyak peneliti. Matilla (2017) meneliti mengenai makna cinta bagi individu dengan disabilitas. Ia menemukan bahwa partisipan penelitiannya memiliki definisi cinta yang spesifik. Penelitian Matilla (2017) mengenai hubungan romantis pada individu dengan disabilitas intelektual menemukan bahwa beberapa dari para partisipannya memiliki pacar, suami, atau istri. Para partisipan ini menggambarkan cinta dari pasangan mereka sebagai sumber berbagi perasaan dan emosi, sumber belajar, dan juga sumber berbagi perhatian (Matilla, 2017). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jones, dkk., (2020), juga menemukan bahwa meskipun proses pencarian cinta pada dewasa muda dengan disabilitas penuh lika-liku, ada pula sebagian dari mereka yang memiliki akhir kisah cinta yang bahagia. Beberapa partisipan dalam penelitian Jones, dkk., (2020), mengungkapkan bahwa cinta sejati mereka adalah orang yang mampu menerima disabilitas yang mereka miliki secara tulus dan tidak merendahkan.
Salah satu partisipan dalam kutipan wawancara yang dilakukan oleh Jones (2020), memaparkan:
“Saya percaya, adalah mungkin untuk menghilangkan ketakutan stereotip akan ketidakmampuan yang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang dengan disabilitas fisik yang parah, caranya adalah dengan mendukung penyandang disabilitas yang putus asa untuk mencari cerita yang menginspirasi.”
Salah satu karya yang dapat dijadikan rujukan dalam menelusuri kisah inspiratif pasangan dengan disabilitas adalah film yang berjudul “What They Don’t “Talk About When They Talk About Love (2013)”. Film yang bercerita tentang kisah cinta pasangan difabel ini memiliki pesan bahwa ada banyak orang yang unggul dalam berbagai bidang kehidupan dan terkadang memandang keunggulan seseorang harus dipisahkan dari keterbatasan fisik. Beranjak dari penelitian dan studi kasus inspiratif dari Barat, di Indonesia, penelitian dan kisah inspiratif mengenai hubungan romantis para individu disabilitas masih sangat minim. Salah satu kisah inspiratif yang berasal dari Indonesia adalah kisah dari Wahyu dan Aslima.
Aslima yang merupakan penyandang disabilitas sejak lahir memiliki pasangan tanpa disabilitas yang mampu memandang kekurangan yang ia miliki melalui sudut pandang yang lain (Kompas, 2014). Perjalanan cinta Aslima sendiri penuh lika-liku, sejak remaja ia sempat mengalami stigma bahwa tidak akan menikah karena keterbatasan fisik yang dialaminya. Namun, alih-alih menyerah, ia justru mengembangkan keahliannya di bidang seni hingga akhirnya dapat hidup secara mandiri. Aslima pun dipertemukan dengan Wahyu melalui seni, hal ini yang menyatukan mereka hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa mandiri. Aslima juga ingin hidup seperti keluarga normal dan berperan sebagai istri pada umumnya, melayani suami, mengurus rumah, dan membesarkan anak-anak.
“Istri saya tak ada bedanya dengan perempuan lain yang badannya lengkap. Ia bisa melakukan semua pekerjaan sendiri,” ujar Wahyu (Kompas, 2014)
Aslima menyelesaikan pekerjaan rumahnya tanpa pembantu, dari mulai membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Ia tidak ingin keterbatasan fisiknya menghalanginya beraktivitas seperti perempuan lain. Ia juga meminta Wahyu untuk mengajari membuat kerajinan akar wangi agar bisa membantu pekerjaan suaminya. Wahyu kini memiliki dua lapak kerajinan dan cinderamata di Dusun Kinahrejo, Cangkringan.
Melalui kisah inspiratif di atas, pesan yang dapat dipetik bagi kita sebagai individu yang hidup di lingkungan beragam adalah untuk saling menghargai dan memandang bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi dirinya. Berdasarkan pesan moral yang didapatkan dari kisah inspiratif tersebut, berikut ini kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk mendukung individu dengan disabilitas agar turut merasakan hubungan yang percintaan yang sehat, antara lain:
- Percaya bahwa mereka dengan disabilitas juga memiliki perasaan dan keinginan untuk mencintai dan dicintai,
- Hargai perasaan mereka dan hindari stigma yang membuat mereka merasa tidak berhak akan perasaan yang dimiliki,
- Percaya bahwa mereka dengan disabilitas juga berhak untuk menikah dan memiliki hubungan jangka panjang yang bahagia,
- Individu dengan disabilitas tidak ingin dipandang berbeda atau sebagai beban dalam hubungan percintaan yang mereka jalin,
- Hindari kata-kata yang dapat menjatuhkan kepercayaan diri mereka saat mendengarkan cerita cinta individu dengan disabilitas,
Pada intinya, ketika individu dengan disabilitas sedang jatuh cinta, hal tersebut adalah bentuk perasaan yang murni dirasakan oleh mereka sama seperti individu pada umumnya. Penelitian Jones, dkk., (2020), mengungkapkan bahwa ketika individu dengan disabilitas percaya diri dalam hubungan romantis yang dijalin, maka ketertarikan dari lawan jenis pada diri mereka akan terpancar. Maka, lakukanlah beberapa tips di atas untuk mendukung kepercayaan diri individu dengan disabilitas dalam menjalin hubungan romantis yang sehat.
Referensi:
Forrester-Jones, R., Bates, C., Skillman, K. M., & Elson, N. (2020). Love and loving relationships: What they mean for people with learning disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 863-863.
Friedman, C. (2019). Intimate relationships of people with disabilities. Inclusion, 7(1), 41-56.
Gischa, S. (2021, 2 Januari). Kisah Sejati Tanpa Memandang Fisik.
Ignagni, E., Fudge Schormans, A., Liddiard, K., & Runswick-Cole, K. (2016). ‘Some people are not allowed to love’: intimate citizenship in the lives of people labeled reference intellectual disabilities. Disability & Society, 31(1), 131-135.
Mattila, J., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2017). ‘Everyone needs love’–an interview study about perceptions of love in people with intellectual disability (ID). International journal of adolescence and youth, 22(3), 296-307.